 Ilustrasi KDRT(Dok.Freepik)
Ilustrasi KDRT(Dok.Freepik)
KOMNAS Perempuan mengapresiasi usulan revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Usulan tersebut disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) karena UU PKDRT dinilai banyak kelemahan dalam menangani kasus KDRT yang jumlahnya cenderung meningkat.
“Komnas Perempuan menghargai usulan tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban KDRT,” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi saat dihubungi, Minggu (17/11).
Komnas Perempuan sendiri, kata Siti, sebagai bagian dari upaya melakukan refleksi 20 tahun UU PKDRT melakukan call for input (Cfi) dari kementerian/lembaga, pendamping korban, dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan UU PKDRT. “Hasil Cfi akan menjadi dasar untuk optimalisasi UU PKDRT atau revisi UU PKDRT,” jelasnya.
Tahun 2024 menjadi penanda dua dasawarsa keberlakuan Undang-Undang PKDRT. UU tersebut disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 14 September 2004 dan diundangkan pada 22 September 2004.
Siti menyampaikan, sejak pengesahan UU PKDRT, Komnas Perempuan mencatat kasus KDRT merupakan yang terbanyak dilaporkan ke Komnas Perempuan dan organisasi pengada layanan. Jenis KDRT terbanyak setiap tahunnya adalah kekerasan terhadap istri (KTI) yang menempati urutan pertama sebanyak 70% dari keseluruhan kasus yang terjadi di ranah personal.
“Hal ini menunjukkan KDRT sebagai tindak pidana telah dikenali oleh masyarakat dan digunakan oleh korban untuk mengklaim keadilan dan pemulihannya,” katanya.
Di samping itu, terdapat sejumlah tren penanganan kasus KDRT. Siti mencontohkan seperti kriminalisasi korban KDRT, KDRT berlanjut (post separation abuse), konflik pengasuhan anak, KDRT pada pernikahan belum tercatat. Kemudian pola penyelesaian KDRT dilaporkan kepada kepolisian, kemudian dicabut dengan menggunakan mekanisme restorative justice, korban memilih perceraian.
Ada juga KDRT yang beririsan dengan kekerasan gender siber (KBGS) yang mana rekaman video intim sering digunakan sebagai alat kontrol, ancaman, dan intimidasi terhadap korban. Belum lagi KDRT yang berujung femisida atau korban menjadi perempuan yang berkonflik dengan hukum.
Tren tersebut, katanya, tidak terlepas dari belum dioptimalkannya ketentuan dalam UU PKDRT seperti perintah perlindungan, program konseling untuk pelaku, perspektif aparat penegak hukum dan pedamping atas KDRT, serta peran serta masyarakat untuk mencegah dan menbantu korban KDRT.
“UU PKDRT tidak memandatkan peraturan pelaksana untuk pelaksanaan perintah perlindungan dan program konseling pelaku yang menyebabkan kedua ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kekerasan memburuk atau menjadi femisida, dan memulihkan pelaku agar memahami dan mengubah perilakunya, belum dapat dijalankan dengan optimal,” pungkasnya. (Ifa/M-3)
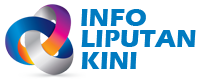
 2 hours ago
1
2 hours ago
1








































