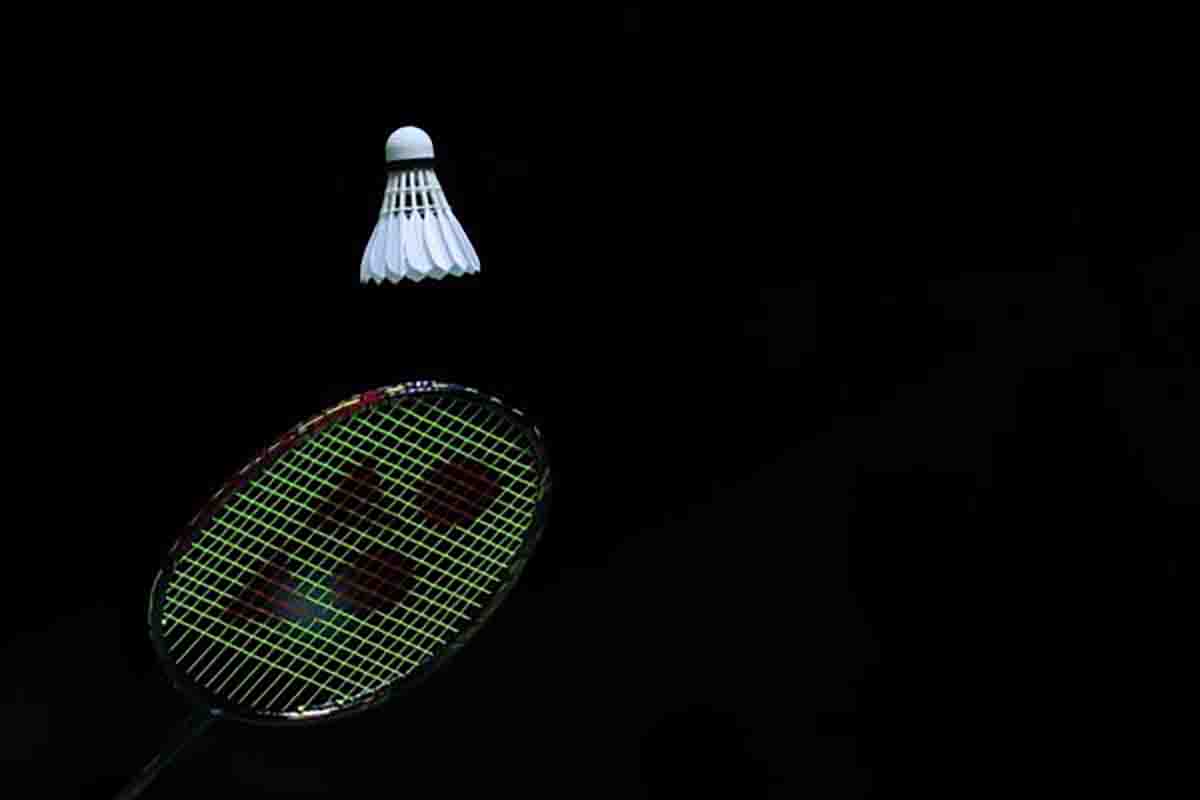(MI/Seno)
(MI/Seno)
INDONESIA kembali menghadapi titik krusial dalam perjalanan politik dan demokrasinya. Di tengah krisis pangan global dan kerentanan sektor pertanian nasional, TNI-AD mengusulkan pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan untuk mengurus pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan.
Program yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto ini diklaim sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi kerawanan pangan. Namun, di balik narasi ‘pembangunan’ dan ‘kedaulatan pangan’, tersembunyi agenda politik yang berpotensi menggerus demokrasi dan mengembalikan militer ke panggung kekuasaan sipil.
Sejarah telah mengajarkan bahwa setiap kali militer melangkah terlalu jauh ke ranah sipil, demokrasi yang lahir dari jerih payah Reformasi 1998 terancam mengalami kemunduran. Doktrin Dwifungsi TNI yang resmi dihapus pasca-1998 kini tampaknya sedang dihidupkan kembali dalam kemasan baru: bukan sebagai kekuatan represif, melainkan sebagai ‘pahlawan pembangunan’. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi sebuah gerakan politis yang perlu dibongkar secara kritis.
DARI DWIFUNGSI KE PEMBANGUNAN TERITORIAL: NOSTALGIA ORBA?
Struktur teritorial TNI (kodam, kodim, koramil) adalah warisan Orde Baru yang dirancang untuk mengawasi masyarakat hingga tingkat desa. Pada era Soeharto, struktur ini berfungsi ganda: sebagai alat pertahanan sekaligus alat kontrol politik. Pasca-Reformasi, TNI secara resmi meninggalkan fungsi sosial-politiknya. Namun, rencana 100 batalion teritorial pembangunan mengisyaratkan bahwa TNI tidak hanya kembali ke desa, tetapi juga mengambil alih peran kementerian sipil.
Ironisnya, program ini muncul di saat anggaran Kementerian Pertanian dipangkas. Alih-alih memperkuat kapasitas petani melalui pendampingan teknis, akses kredit, atau reformasi agraria, pemerintah justru memilih militerisasi sektor pangan. Ini adalah bentuk pengalihan wewenang yang berbahaya.
Pertanyaannya: mengapa TNI, yang tidak memiliki kompetensi teknis di bidang pertanian, diberi mandat mengurus pangan? Apakah ini pengakuan tidak langsung bahwa birokrasi sipil gagal—atau justru upaya untuk mengebiri peran kementerian sipil demi memperluas hegemoni militer?
PRABOWO DAN TNI-AD: SIMBIOSIS MUTUALISME POLITIK
Prabowo Subianto bukanlah politikus biasa. Ia mantan jenderal yang karier militernya diwarnai kontroversi, sekaligus politikus yang memahami betul cara bermain di dua dunia: militer dan elektoral. Dukungannya terhadap program 100 batalion teritorial tidak bisa dilepaskan dari dua kepentingan: konsolidasi kekuasaan internal di tubuh TNI dan pembangunan citra sebagai pemimpin yang tegas dan solutif.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo membutuhkan dukungan politik yang solid. TNI-AD, dengan 100 batalion teritorialnya, bisa menjadi tulang punggung bagi stabilitas rezim. Dalam jangka pendek, program ini mungkin akan dipromosikan sebagai keberhasilan ‘revolusi pangan’. Namun, dalam jangka panjang, ia berpotensi menjadi alat untuk mengamankan loyalitas internal TNI dan membangun jaringan patronase di perdesaan. Ingat, setiap batalion teritorial bukan hanya sekadar unit pertanian—mereka adalah struktur komando yang terhubung langsung dengan hierarki militer.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa program ini adalah investasi politik Prabowo untuk lima tahun ke depan. Jika TNI sukses ‘membagikan’ beras murah atau pupuk subsidi melalui batalion teritorial, narasi ‘Prabowo-feeding-the-nation’ akan mudah dikapitalisasi sebagai modal elektoral. Di saat yang sama, kritik terhadap pemerintah bisa dilumpuhkan dengan dalih ‘mengganggu ketahanan pangan’.
MILITERISASI KEBIJAKAN PUBLIK: ANCAMAN BAGI DEMOKRASI
Bahaya terbesar dari program ini bukan hanya pada potensi korupsi atau inefisiensi, melainkan pada normalisasi peran militer di ruang sipil. Jika menguasai produksi dan distribusi pangan, TNI akan memegang kendali atas hajat hidup orang banyak. Ini adalah kekuasaan yang sangat politis. Masyarakat yang bergantung pada program TNI akan sulit bersuara kritis karena setiap protes bisa dianggap sebagai ‘ancaman bagi ketahanan nasional’.
Lebih mengkhawatirkan lagi, program ini bisa menjadi pintu masuk bagi militerisasi konflik agraria. Indonesia memiliki sejarah kelam di mana TNI terlibat dalam sengketa lahan, baik sebagai aktor langsung maupun sebagai ‘penjaga keamanan’ korporasi. Dengan mandat mengurus pertanian, batalion teritorial berpotensi mengambil alih lahan-lahan strategis atas nama ‘program pangan’, yang pada praktiknya bisa disalahgunakan untuk kepentingan bisnis oknum tertentu.
Belum lagi persoalan akuntabilitas. Anggaran untuk 100 batalion teritorial harus diawasi ketat. Tetapi, siapa yang berani mengaudit TNI? Berbeda dengan kementerian sipil yang wajib melaporkan ke DPR dan BPK, anggaran militer sering kali dikelilingi tembok kerahasiaan dengan dalih ‘keamanan nasional’. Jika tidak ada transparansi, program pembangunan ini bisa menjadi lahan basah korupsi baru.
MENGAPA KITA HARUS WASPADA?
Argumen bahwa TNI lebih disiplin dan efisien adalah jebakan retorika. Persoalan pangan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik yang mengedepankan komando dan kontrol. Ketahanan pangan membutuhkan partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, reformasi agraria, dan tata kelola yang inklusif—bukan sekadar proyek menanam padi atau beternak sapi oleh para serdadu.
Selain itu, melibatkan TNI dalam urusan sipil adalah pengkhianatan terhadap Reformasi 1998. Kita telah bersusah payah memisahkan militer dari politik, dan kini langkah mundur itu sedang terjadi. Jika hari ini TNI boleh mengurus pangan, besok mereka bisa mengeklaim hak mengurus pendidikan, kesehatan, atau bahkan energi. Di mana batasnya?
PERLAWANAN ATAU PEMBIARAN?
Program 100 batalion teritorial ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan sinyal kembalinya militer ke ruang sipil dengan dalih ketahanan pangan. Jika ini dibiarkan, kita sedang membuka jalan bagi militerisasi kebijakan publik yang melampaui batas konstitusionalnya.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah program ini akan berjalan, melainkan seberapa jauh masyarakat sipil akan membiarkannya. Akankah kita hanya menjadi saksi dari normalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, ataukah kita berani menuntut transparansi, akuntabilitas, dan batasan yang jelas terhadap peran TNI?
Jika demokrasi ingin tetap bertahan, batas antara militer dan sipil harus dijaga. Jangan biarkan narasi pembangunan dan kedaulatan pangan menjadi dalih bagi TNI untuk kembali mencengkeram kehidupan sipil. Karena, jika kita lengah, kelak kita mungkin akan bertanya: sejak kapan negeri ini kembali tunduk pada seragam hijau?
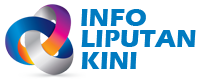
 1 day ago
5
1 day ago
5