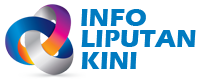ilustrasi.(MI)
ilustrasi.(MI)
PAKAR Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto bukan sekadar perdebatan simbolik, melainkan menjadi alarm bahaya bagi arah demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hal itu disampaikan Bivitri dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (4/11). Ia menilai, pemberian gelar tersebut berpotensi menjadi "pathway" atau jalan kembali ke sistem pemerintahan otoriter seperti era Orde Baru, bahkan membuka kemungkinan untuk menghidupkan kembali UUD 1945 naskah awal sebelum amandemen.
“Ini semacam alarm sebetulnya, kami menyebutnya semacam pathway untuk kembali kepada UUD yang lama naskah awal yang dibuat pada Juli 1945,” ujar Bivitri.
Menurut dia, seluruh proses amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 justru dilahirkan sebagai koreksi terhadap praktik kekuasaan panjang Soeharto selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.
“Kalau teman-teman ingat, hal pertama yang diubah dalam amandemen UUD 1945 adalah pembatasan masa jabatan presiden, dari tak terhingga menjadi dua kali. Itu belajar dari Soeharto,” jelasnya.
Selain pembatasan masa jabatan, Bivitri menambahkan, berbagai lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lahir dari semangat reformasi untuk mencegah terulangnya konsentrasi kekuasaan di satu tangan.
“Bayangkan kalau legitimasi perubahan UUD 45 itu hilang karena Soeharto justru dianggap pahlawan. Itu jalan yang sangat mulus tanpa kerikil untuk balik ke UUD 1945 naskah awal. Kalau balik ke naskah awal, kita tidak punya MK, tidak ada lagi pasal-pasal HAM, tidak ada pembatasan masa jabatan, tidak ada KPU seperti sekarang. Itu mengerikan,” lanjutnya.
Bivitri menegaskan, usulan pemberian gelar kepada Soeharto tidak hanya bermasalah secara moral dan politik, tetapi juga tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Menurutnya, setelah amandemen UUD 1945 selesai pada 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR) baru, kecuali yang bersifat internal.
“Kalau dikatakan legalitasnya sudah legal, itu salah. Karena TAP MPR sejak 2002 tidak boleh lagi keluar. Jadi kalau ada perubahan pada TAP MPR yang mengatur soal pengadilan Soeharto, itu tidak mungkin,” tegasnya.
Bivitri juga menyebut tim advokasi yang menolak pemberian gelar, termasuk jaringan masyarakat sipil, telah menelusuri bahwa tidak ada dokumen resmi terkait perubahan TAP MPR yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pengusulan gelar tersebut.
“Yang terjadi itu hanya pidato Pak Bamsoet (Ketua MPR). Tapi kalau dikatakan sudah legal secara hukum, ya keliru,” ujarnya.
Bivitri menilai, upaya mengangkat Soeharto sebagai pahlawan merupakan bentuk distorsi sejarah dan ancaman terhadap hasil reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
“Sebagai orang yang belajar hukum tata negara, ini mengerikan. Tapi mestinya bukan cuma mengerikan bagi kami, melainkan bagi kita semua,” pungkasnya. (Cah/P-3)