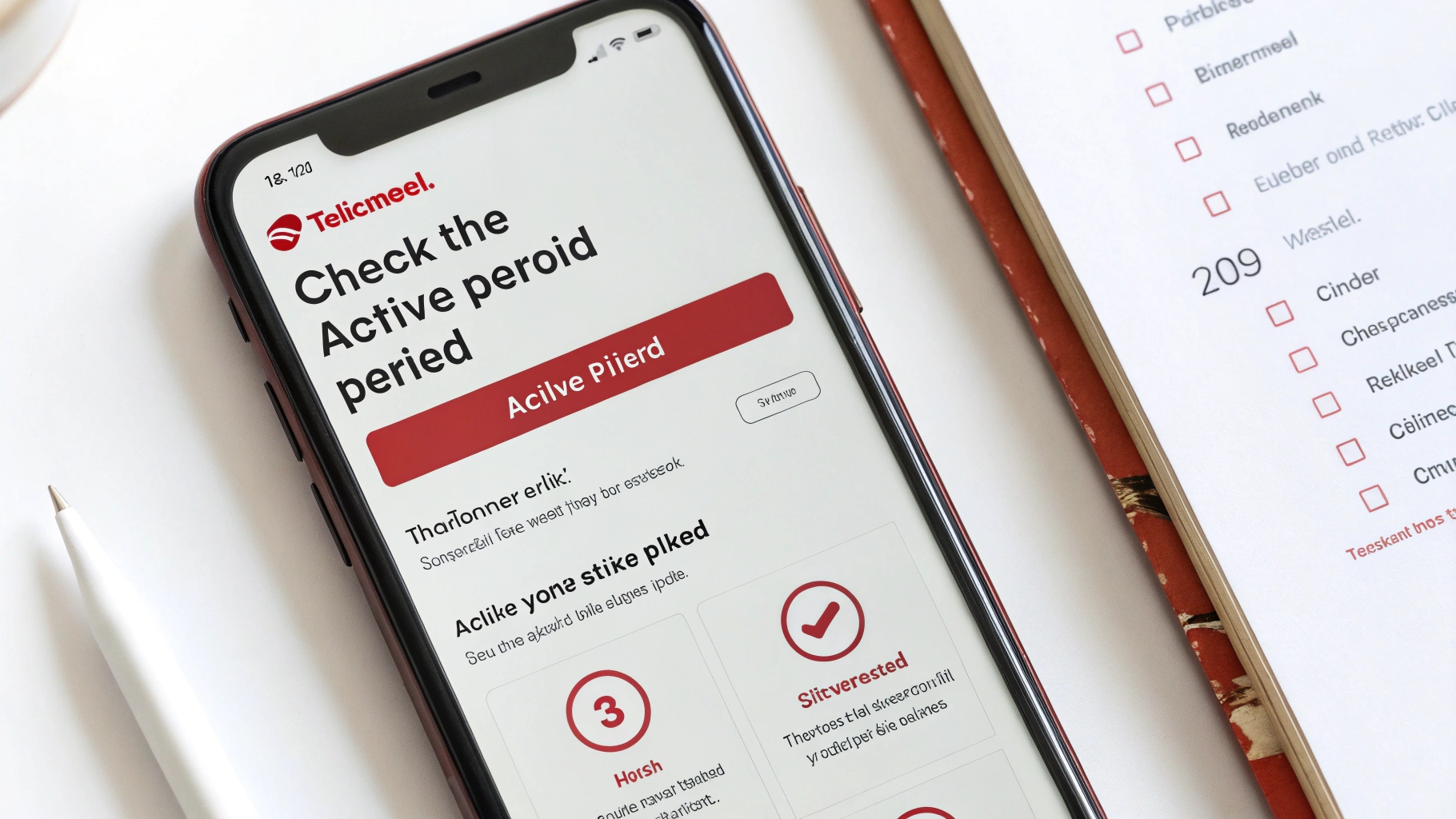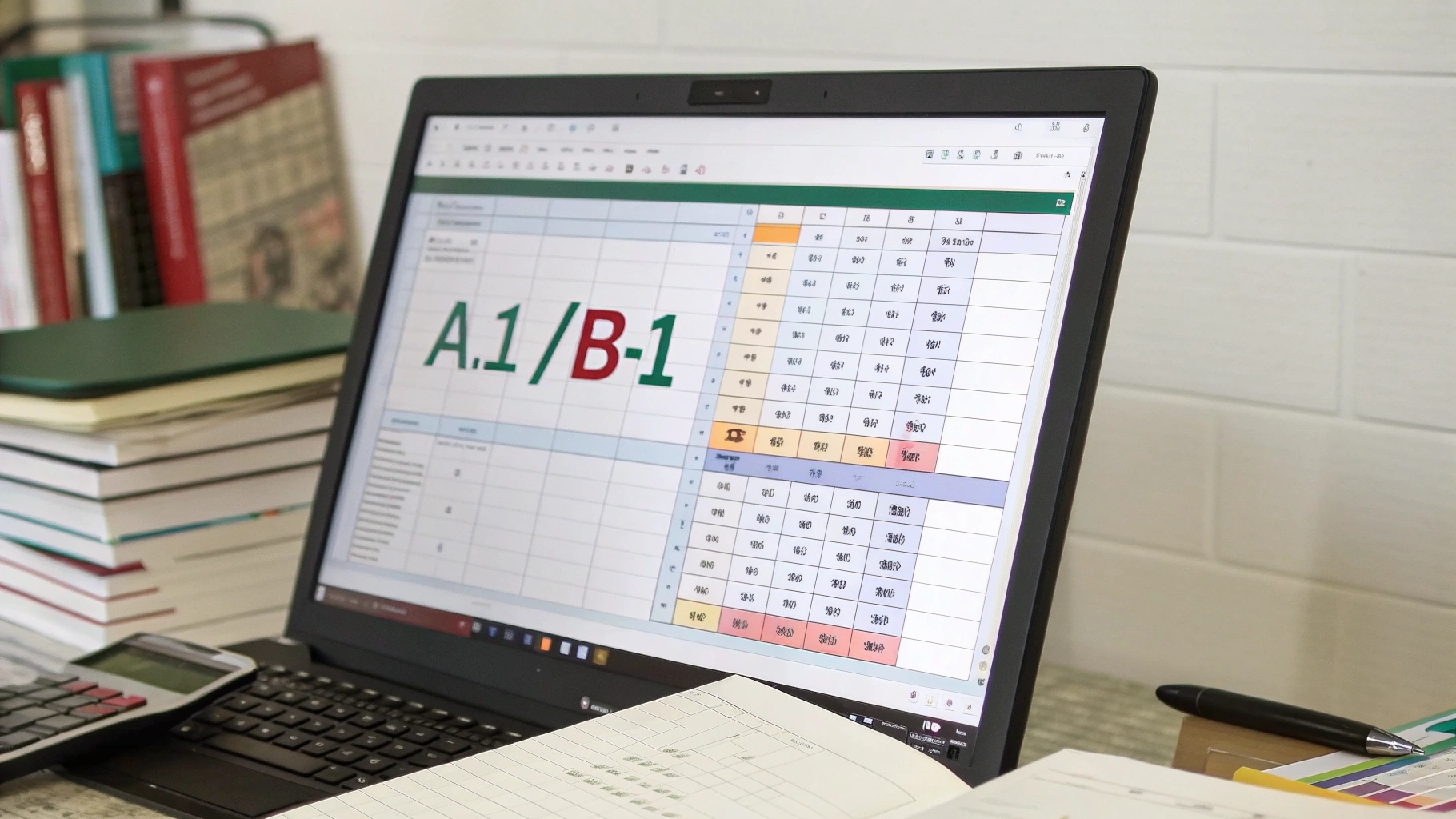Hamim Pou Ahli Kebijakan Publik(Dok. Pribadi)
Hamim Pou Ahli Kebijakan Publik(Dok. Pribadi)
INDONESIA baru saja mendapat pelajaran mahal tentang bagaimana sebuah niat baik bisa tersesat di lorong kebijakan. Ketika Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 sebagai tersangka perkara pengadaan perangkat berbasis ChromeOS, publik kembali bertanya: apakah triliunan rupiah yang kita keluarkan benar-benar berubah menjadi jam belajar bermutu, atau hanya berhenti sebagai angka di lembar kontrak? Pertanyaan ini layak dijawab dengan kepala dingin, data resmi, dan keberpihakan pada murid serta guru.
Semua angka pokoknya jelas. Kejaksaan Agung dalam ekspos perkara menyebut perkiraan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,98 triliun seraya menegaskan hitungan final masih menunggu proses audit lebih lanjut. Pada konferensi pers pertengahan Juli 2025, pejabat penyidik menerangkan total nilai pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis Chromebook pada periode 2019–2022 berada di kisaran Rp9,3 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Dana Alokasi Khusus pendidikan. Di sisi lain, pernyataan resmi sang menteri pada Juni 2025 mencatat perangkat telah terdistribusi sebanyak 97% ke sekitar 77 ribu sekolah pada 2023. Rangkaian data ini mengikat dua fakta: skala belanja sangat besar, dan janji manfaat yang sedianya terasa langsung di kelas.
Namun, inti persoalan bukan sekadar ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Bagi tata kelola publik, yang lebih menentukan adalah apakah keputusan belanja mengikuti prinsip kompetisi yang adil, analisis biaya seumur hidup kepemilikan atau total cost of ownership, dan pembuktian kemanfaatan belajar. Total cost of ownership bukan istilah manajemen mengawang. Ia mewajibkan pemerintah menghitung seluruh biaya selama masa pakai perangkat, mulai dari harga unit, lisensi, pengelolaan dan keamanan, konektivitas dan kapasitas jaringan, pelatihan tenaga pengajar, layanan purna jual, hingga penggantian.
Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sering kita sebut 3T, angka ini cenderung meningkat karena akses internet tak stabil, kebutuhan kunjungan teknisi, dan penyediaan konten luring. Keputusan yang baik seharusnya menguji dan membandingkan total cost of ownership lintas ekosistem—ChromeOS, Windows, Android—berdasarkan fungsi: mengetik, presentasi, akses konten literasi dan numerasi, kompatibilitas Asesmen Nasional Berbasis Komputer, sensitivitas terhadap kualitas jaringan, ketahanan baterai, dan jam pakai efektif per minggu.
Di titik ini, spesifikasi teknis menjadi ujian integritas. Hukum pengadaan melarang syarat yang mengarah pada merek atau produk tertentu, kecuali dengan justifikasi yang tidak terbantahkan. Spesifikasi fungsional adalah kuncinya: negara menulis kebutuhan, bukan preferensi merek. Rumusan semisal “perangkat mampu menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer; memiliki manajemen perangkat jarak jauh; kompatibel dengan konten pembelajaran; dan sanggup bekerja andal pada konektivitas yang fluktuatif” akan menjaga kompetisi.
Inilah ruh yang semestinya dijaga oleh jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah serta diawasi secara kuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memang diperlukan untuk kepatuhan administratif, tetapi ia tidak boleh berubah menjadi pemberi stempel teknis yang de facto mengunci pasar pada satu ekosistem. Setiap nota pendampingan harus eksplisit non-mengikat, netral-tekno, dan tidak menetes menjadi kewajiban terselubung dalam juknis atau persyaratan Dana Alokasi Khusus.
Bagaimana dengan manfaat di kelas? Distribusi 97% patut diapresiasi sebagai kerja logistik. Tetapi kelas bukan gudang. Di banyak sekolah, terutama pada wilayah 3T, perangkat yang sangat bergantung pada internet stabil akan segera menabrak tembok realitas. Keluhan guru tentang keterbatasan memasang aplikasi pelengkap atau mengelola akun di luar ekosistem resmi adalah alarm dini. Tanpa jaminan jaringan, pelatihan yang merata, dan dukungan layanan yang cepat, perangkat akan mengalami demosi fungsi: dari alat pembelajaran harian menjadi sekadar piranti untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer setahun sekali. Padahal Asesmen Nasional Berbasis Komputer sendiri adalah instrumen evaluasi sistem—bukan tujuan belajar itu sendiri. Program ini, sesuai penjelasan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memotret mutu pendidikan melalui tiga instrumen: Asesmen Kompetensi Minimum untuk literasi membaca dan numerasi, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Bila perangkat hanya hidup pada musim asesmen, kita gagal mengubah teknologi menjadi kebiasaan belajar.
Karena itu, pembenahan ke depan mesti dimulai dari cara negara menghitung manfaat. Ukuran yang relevan bukan banyaknya unit terkirim, melainkan biaya per jam belajar efektif. Pemerintah bisa dan harus merancang uji coba multiekosistem minimal dua semester pada klaster sekolah dengan kualitas jaringan berbeda. Indikatornya terang: kenaikan jam pakai mingguan nyata di kelas, perbaikan tugas dan presentasi siswa, kemudahan guru menyiapkan bahan ajar, dan keberhasilan menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer tanpa mengorbankan pembelajaran reguler. Hanya bila ambang efisiensi dan reliabilitas tercapai, ekspansi nasional layak dilanjutkan.
Transparansi adalah fondasi. Publik berhak mengetahui rincian harga satuan, komponen lisensi, biaya logistik, standar layanan purna jual, dan performa pascaterima. Di era belanja elektronik, analitik forensik pengadaan perlu ditingkatkan—mulai dari jejak perubahan dokumen, relasi waktu rapat dengan penyusunan spesifikasi, hingga pola transaksi antarpemasok. Lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu dipersenjatai perangkat analisis berbasis data agar mampu mendeteksi penguncian spesifikasi yang canggih, sementara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memperkuat aturan interoperabilitas dan portabilitas data agar negara tidak terkunci pada satu vendor ketika kontrak berakhir. Kontrak teknologi informasi pemerintahan wajib memuat klausul antiketergantungan: standar terbuka, mekanisme keluar yang murah, dan kewajiban pemasok untuk memastikan data dapat berpindah sistem tanpa biaya berlebihan.
Langkah berikutnya menyentuh prasyarat paling dasar: konektivitas. Membeli perangkat tanpa mengatasi persoalan jaringan adalah seperti membangun bandara tanpa landasan pacu. Pada daerah yang belum siap, strategi luring utama—konten tersimpan, sinkronisasi berkala—harus didahulukan, diiringi peningkatan kapasitas jaringan sekolah secara bertahap. Barulah kemudian pelatihan guru diberikan dalam dosis kecil tetapi berulang, terukur oleh praktik kelas, serta didukung pusat bantuan yang responsif, bukan seremoni satu kali yang segera dilupakan.
Akhirnya, marilah kita luruskan tujuan. Digitalisasi pendidikan bukan perlombaan belanja tercepat, melainkan ketekunan mengubah anggaran menjadi pengalaman belajar yang nyata. Negara wajib memastikan prosedur adil, biaya seumur hidup terhitung jujur, dan manfaat terukur dengan instrumen evaluasi yang sahih. Bila itu semua dijalankan, maka perangkat apa pun—apakah berbasis ChromeOS, Windows, atau Android—sekadar menjadi sarana untuk sebuah misi yang lebih mulia: literasi yang dalam, numerasi yang kokoh, karakter yang tumbuh, dan kepercayaan publik yang terawat.
Hook yang seharusnya menghentak kita sederhana: anak-anak Indonesia tidak membutuhkan komputer untuk difoto, mereka membutuhkan perangkat yang menyala setiap jam pelajaran. Ketika kebijakan kembali ke akal sehat—kompetisi yang adil, kontrak yang melindungi pilihan publik, serta pengukuran manfaat yang tidak bisa dimanipulasi—barulah kita dapat mengatakan bahwa anggaran pendidikan benar-benar bekerja untuk masa depan republik. (H-4)
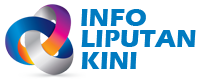
 3 hours ago
3
3 hours ago
3