 Henny Triyani, Nikole Edmonda Yapputro, Reni Juniarsa Pranata, Regine Caitlyn Suwu, P. Tommy Y. S. Suyasa(Dok. Pribadi)
Henny Triyani, Nikole Edmonda Yapputro, Reni Juniarsa Pranata, Regine Caitlyn Suwu, P. Tommy Y. S. Suyasa(Dok. Pribadi)
PADA 2025, dunia jagat maya diramaikan oleh berbagai pertandingan liga sepak bola. Contohnya, liga Inggris dengan pertandingan Newcastle United vs Liverpool yang mengundang lebih dari 200 ribu pencarian di Google Trends. Maraknya pertandingan tersebut membuat para penggemar mengandalkan berbagai prediksi untuk meramalkan kemenangan tim sepakbola favoritnya. Ramalan mengenai kemenangan tim sepak bola dapat berasal dari dukun, cenayang, orang pintar, atau bahkan seorang “anak indigo” sekalipun.
Sebagai contoh, ada seorang anak indigo yang mencoba untuk meramalkan kemenangan Timnas Indonesia saat melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U-23. Namun, ramalan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Indonesia ternyata mengalami kekalahan. Kekalahan Indonesia yang berbanding terbalik dengan ramalan anak indigo tersebut dapat memberikan stigma negatif kepada anak indigo lainnya.
Anak indigo adalah anak yang memiliki karakteristik psikologis berbeda dari anak pada umumnya (Carroll & Tober, 1999). Anak dapat dikatakan sebagai indigo apabila menunjukkan kecenderungan (Virtue, 2001) sebagai berikut: (a) lebih banyak menggunakan intuisi dan imajinasi; (b) memiliki kemampuan psikis/supranatural (merasakan hal-hal gaib); (c) merasa tidak dipahami terkait dengan kemampuan khusus yang dimilikinya; (d) rentan mengalami insomnia (kekurangan tidur), mimpi buruk, kesulitan atau ketakutan untuk tertidur; serta (e) berpotensi disebut sebagai gifted children dan highly sensitive person (HSP).
Namun demikian, kelima karakteristik di atas bervariasi pada setiap anak indigo. Variasi ini berpotensi membuat orang tua mengalami kesalahan persepsi. Misalnya, anak sulit fokus, sulit diam, sulit tidur, suka menginterupsi, suka berimajinasi, dan lain-lain. Dengan ciri-ciri tersebut, orang tua langsung memberikan label “indigo” pada anaknya tanpa mempertimbangkan kecenderungan lainnya.
Pemberian label indigo masih berdampak lebih baik dibandingkan dengan pemberian diagnosis psikopatologis. Namun, pemberian label indigo tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif. Label indigo dapat membuat orang tua memandang anaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah (Lench et al., 2011). Anak juga akan dipandang lebih banyak mengalami peristiwa negatif dalam hidupnya, seperti mengalami masalah di sekolah. Dengan kata lain, pemberian label indigo tidak membuat anak sepenuhnya menjadi positif.
Oleh karena itu, orang tua perlu berhati-hati dalam memberikan label. Pemberian label dapat menimbulkan konsekuensi. Untuk mengantisipasi konsekuensi dari pemberian label tersebut, orang tua dapat mengikuti lima langkah: Selidiki, Arahkan, Dampingi, Akomodasikan, dan Rekatkan atau disingkat “SADAR”. Penjelasan dari kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Selidiki perilaku anak dengan bijak.
Ketika perilaku anak tampak berbeda dari anak lain pada umumnya, seperti memiliki sensitivitas dan kreativitas yang tinggi, minat yang berbeda, hiperaktif, serta suka menyendiri, hindari untuk langsung memberikan label pada anak. Anak perlu diamati perilakunya secara menyeluruh dan konsisten di berbagai situasi. Di berbagai situasi ini, perhatikan apakah pola perilakunya yang berbeda tersebut muncul hanya sesekali atau terus-menerus; serta apakah perilaku tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari.
2. Arahkan anak ke pendampingan profesional.
Setiap anak dikaruniai keunikannya masing-masing. Namun, ketika orang tua menyadari bahwa perilaku anaknya tampak berbeda dari anak lain pada umumnya, orang tua dapat membawa anak kepada seorang profesional. Alih-alih melabeli anak, orang tua dapat membawa anaknya kepada psikolog. Melalui psikolog, orang tua dapat berharap memperoleh penilaian yang lebih objektif dan tepat secara ilmiah. Dengan demikian, anak juga akan memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan bakat dan minatnya.
3. Dampingi anak dengan penerimaan, bukan desakan.
Ketika anak memang dinyatakan mengalami gangguan atau memiliki kebutuhan khusus, orang tua perlu menerimanya dengan berbesar hati. Untuk dapat berbesar hati, orang tua perlu berfokus pada kelebihan/keistimewaan anak, bukan kekurangannya. Dengan demikian, orang tua perlu mendampingi anak hingga kelebihan/keistimewaannya dapat teridentifikasi dan bertumbuh. Percayalah bahwa setiap anak bagaikan tanaman yang akan bertumbuh, berbunga, dan bermekaran dengan indah pada waktunya.
4. Akomodasikan kebutuhan anak secara fleksibel.
Setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Mengakomodasikan kebutuhan anak sama dengan menyesuaikan pola pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran yang diberikan kepada anak. Pola pengasuhan, pendidikan, dan pengajaran ini dapat dipenuhi oleh orang tua secara fleksibel. Alih-alih menganggap bahwa setiap anak adalah sama, orang tua dapat secara optimal memberikan ruang dan pendekatan yang sesuai agar anak dapat berkembang sesuai dengan kelebihan/keistimewaannya masing-masing.
5. Rekatkan identitas anak sesuai dengan realita.
Perkembangan anak yang optimal ditandai dengan konsep diri positif. Konsep diri positif adalah kondisi ketika realitas mendekati sesuatu yang diidealkan. Sesuatu yang diidealkan, misalnya, (a) mampu mengikuti norma rumah, sekolah, dan masyarakat; (b) dapat bersosialisasi dengan baik/mau berbagi; (c) dapat menjaga kesehatan; (d) mendapatkan skor di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM); (e) memiliki keahlian/keterampilan; serta (f) dapat mengurus diri sendiri.
Dengan menerapkan langkah “SADAR” di atas, anak diharapkan dapat bertumbuh mencapai cita-cita sesuai dengan kelebihan/keistimewaannya masing-masing. Sehubungan dengan berbagai momen/liga bola saat ini, anak tidak hanya diajak untuk memprediksi/meramal menang-kalah tim sepak bola favoritnya, tetapi juga diajak berdiskusi mengenai peluang profesi yang mungkin diminati. Apakah anak berminat menjadi pemain bola, wasit, pelatih, manajer, ahli medis, security, event organizer, pengusaha/sponsor, wartawan, ball boy, videographer, photographer, desainer jersey sepak bola, komentator, cleaning service, pemandu sorak/penari, groundskeeper, penyanyi/pemusik, dan lain sebagainya.
Oleh:
Henny Triyani (Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara)
Nikole Edmonda Yapputro (Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara)
Reni Juniarsa Pranata (Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara)
Regine Caitlyn Suwu (Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara)
P. Tommy Y. S. Suyasa (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara)
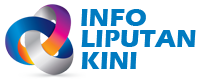
 5 hours ago
3
5 hours ago
3
















































