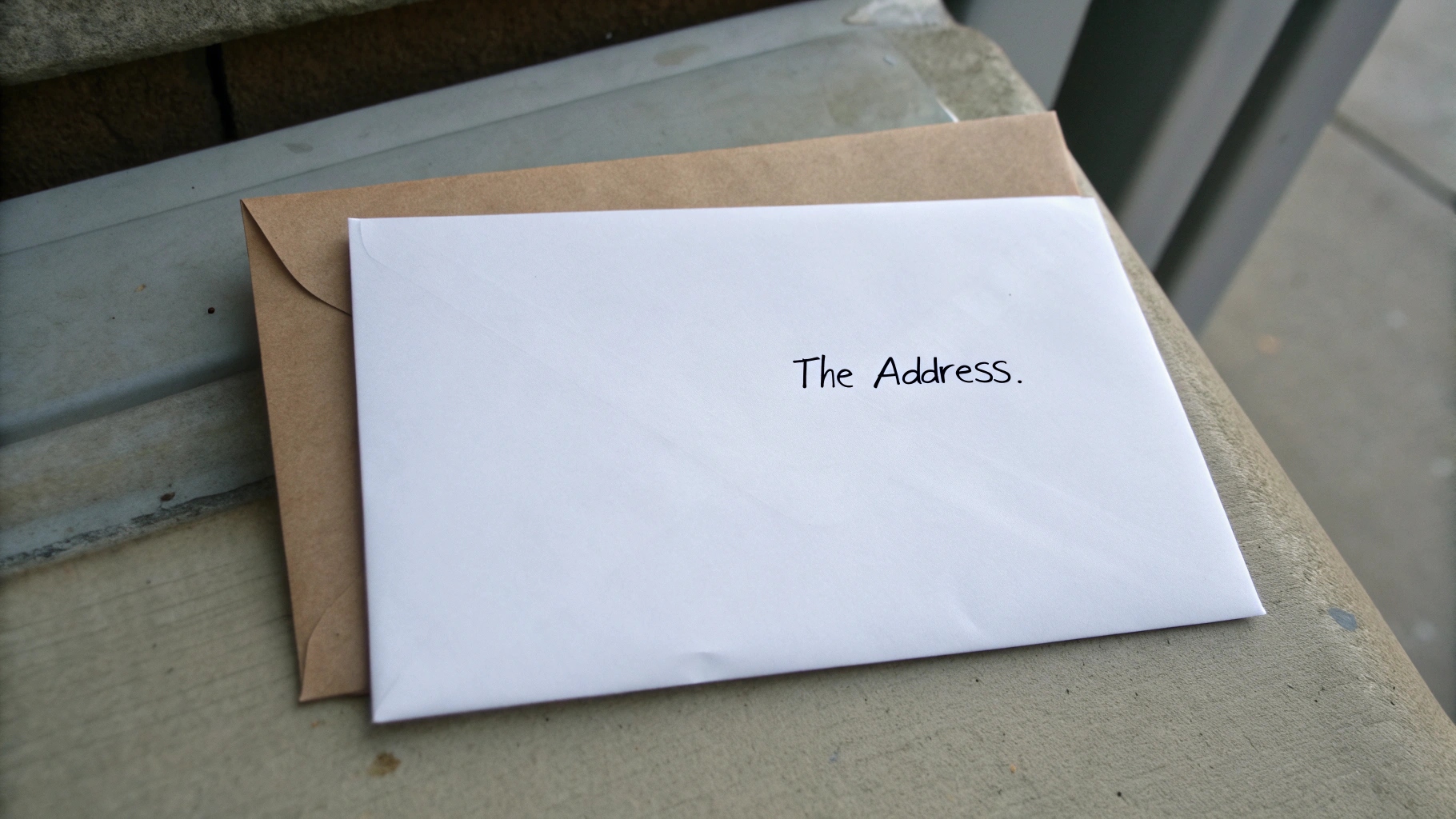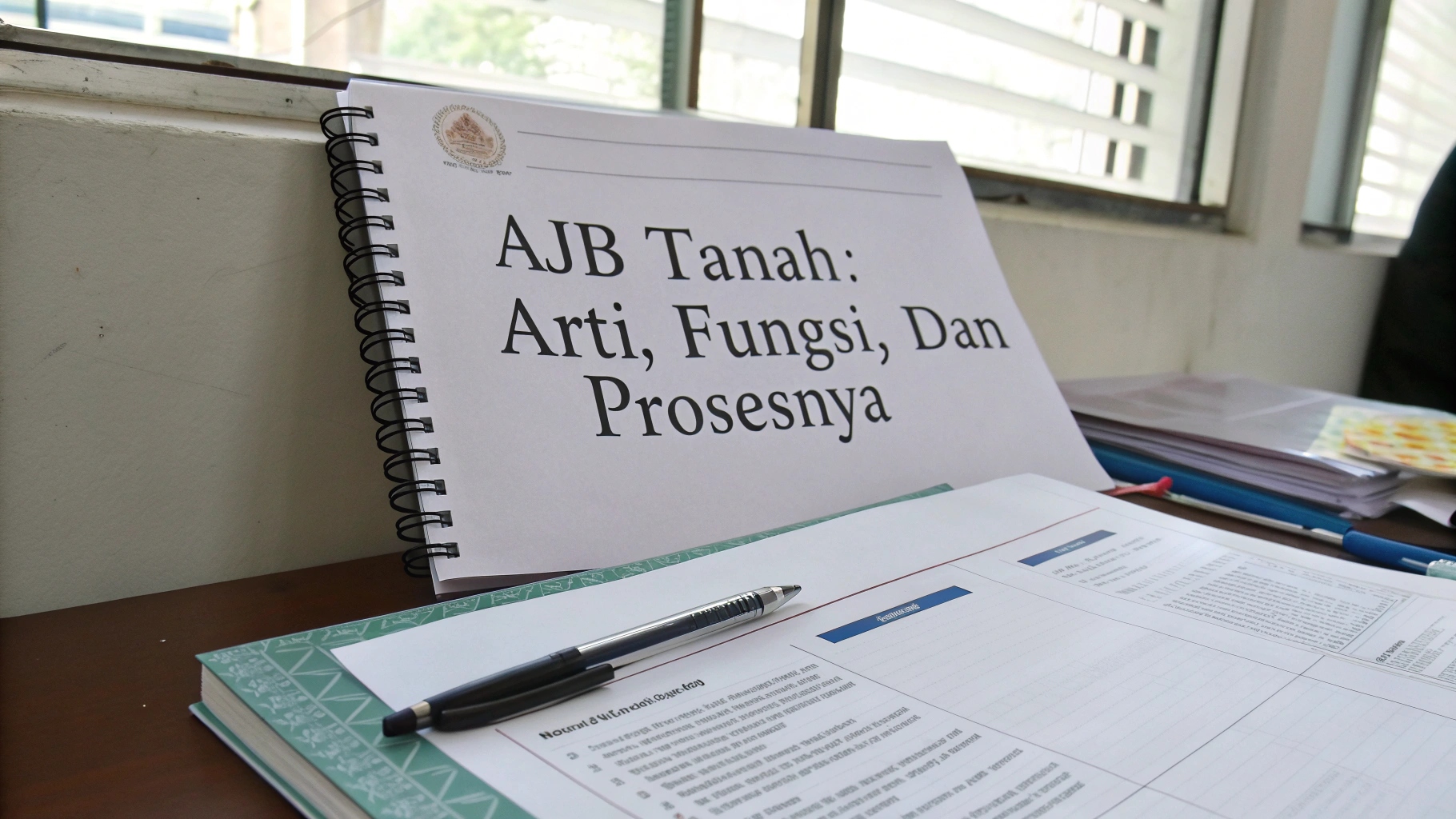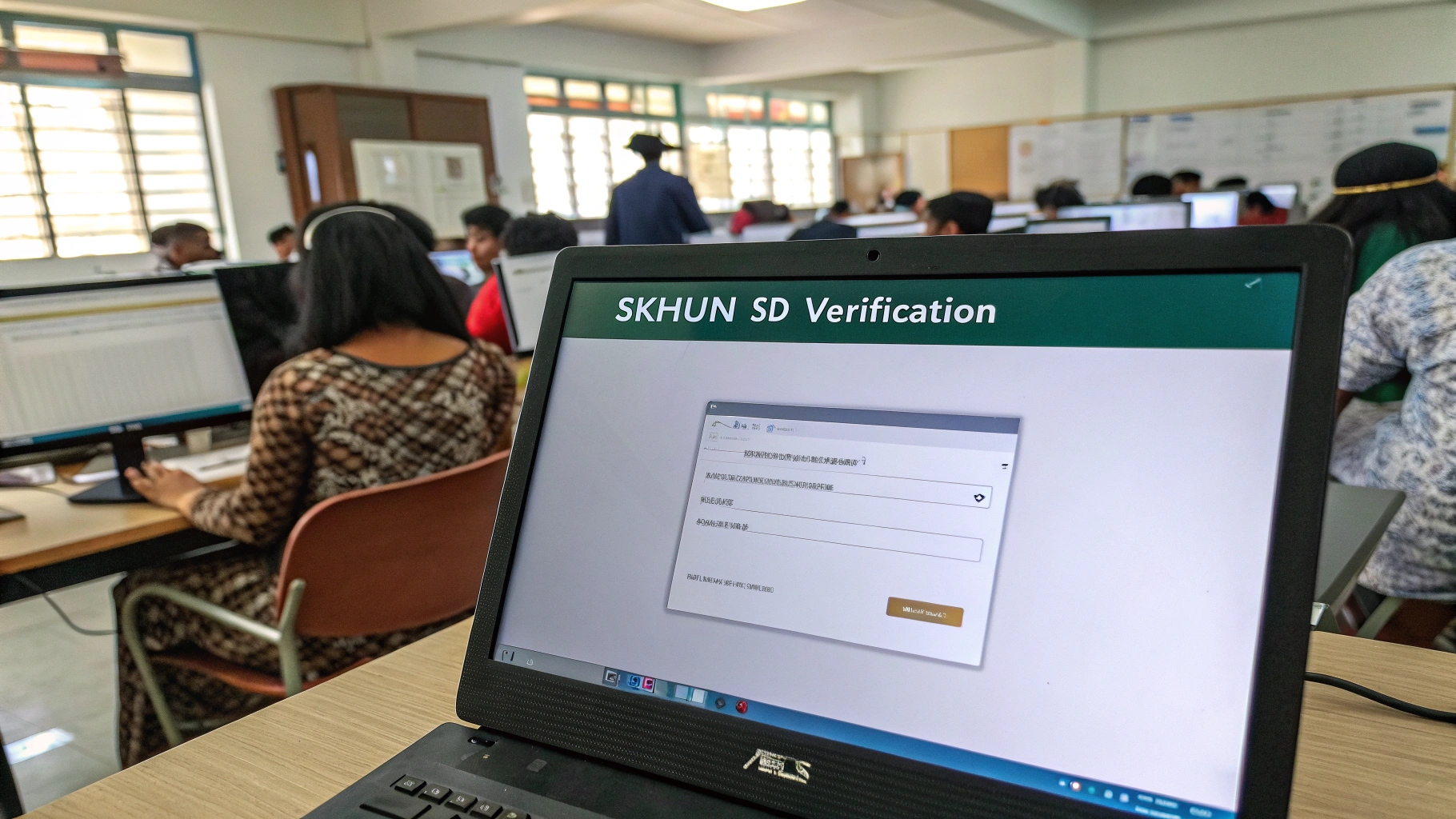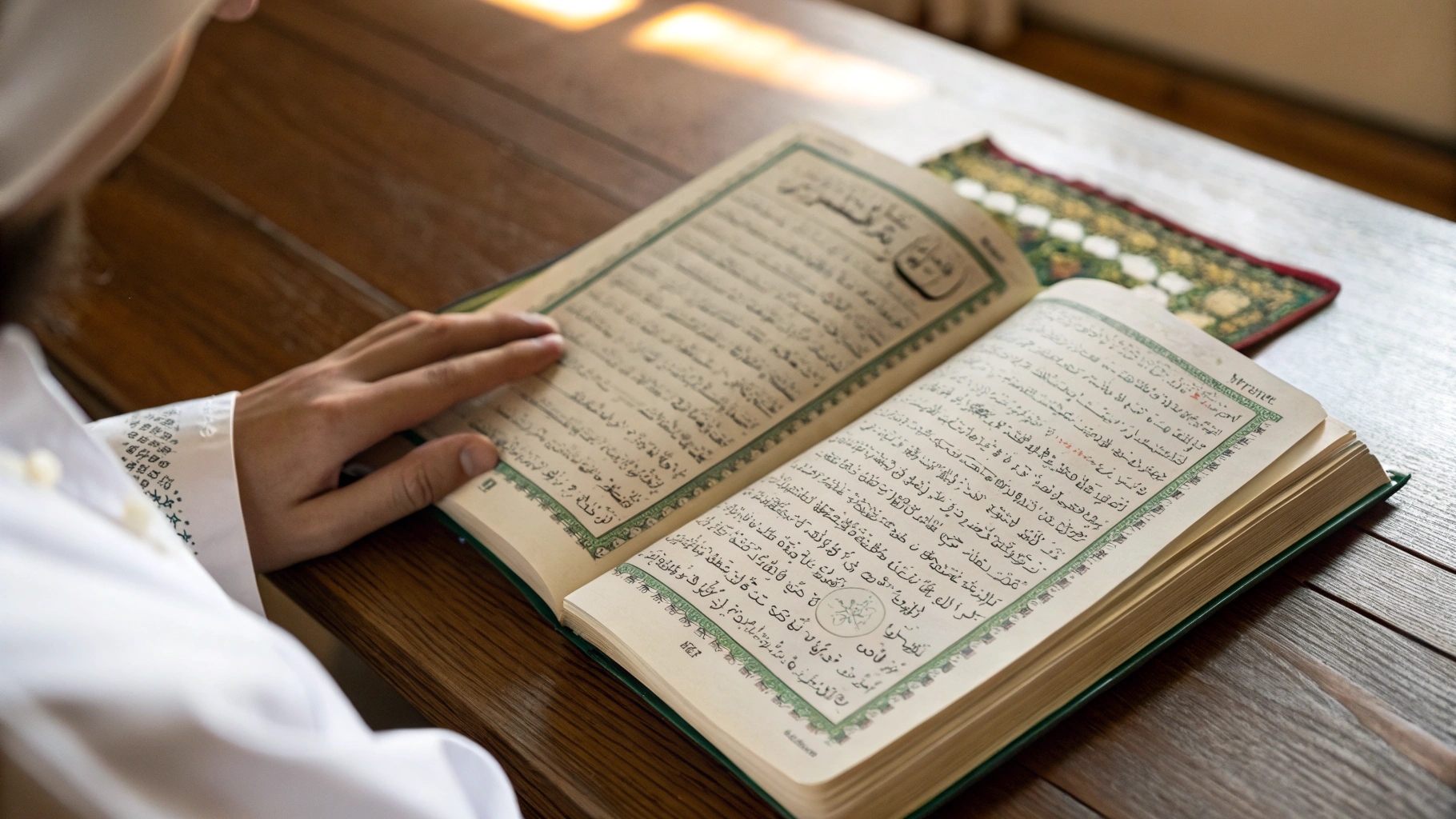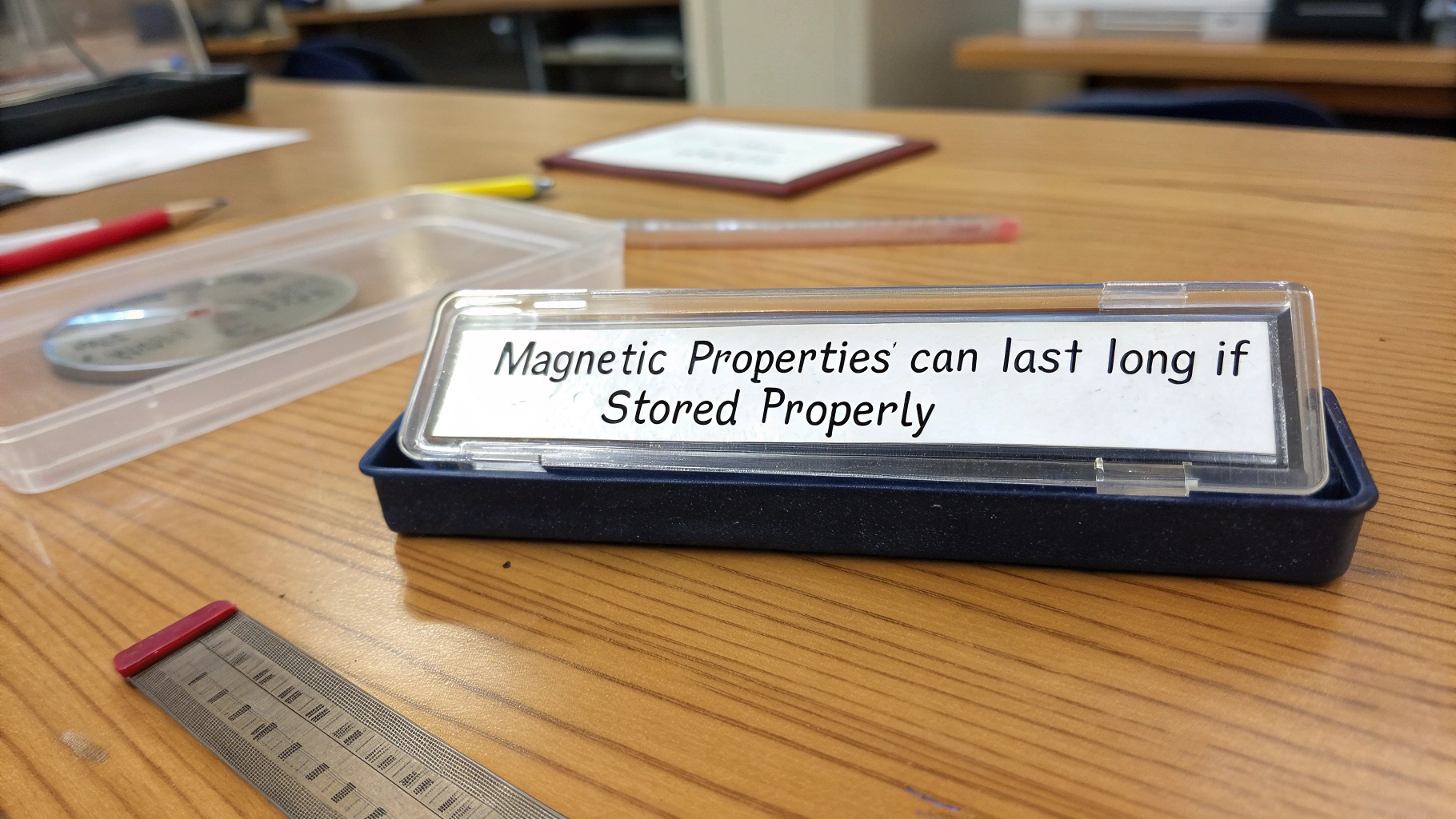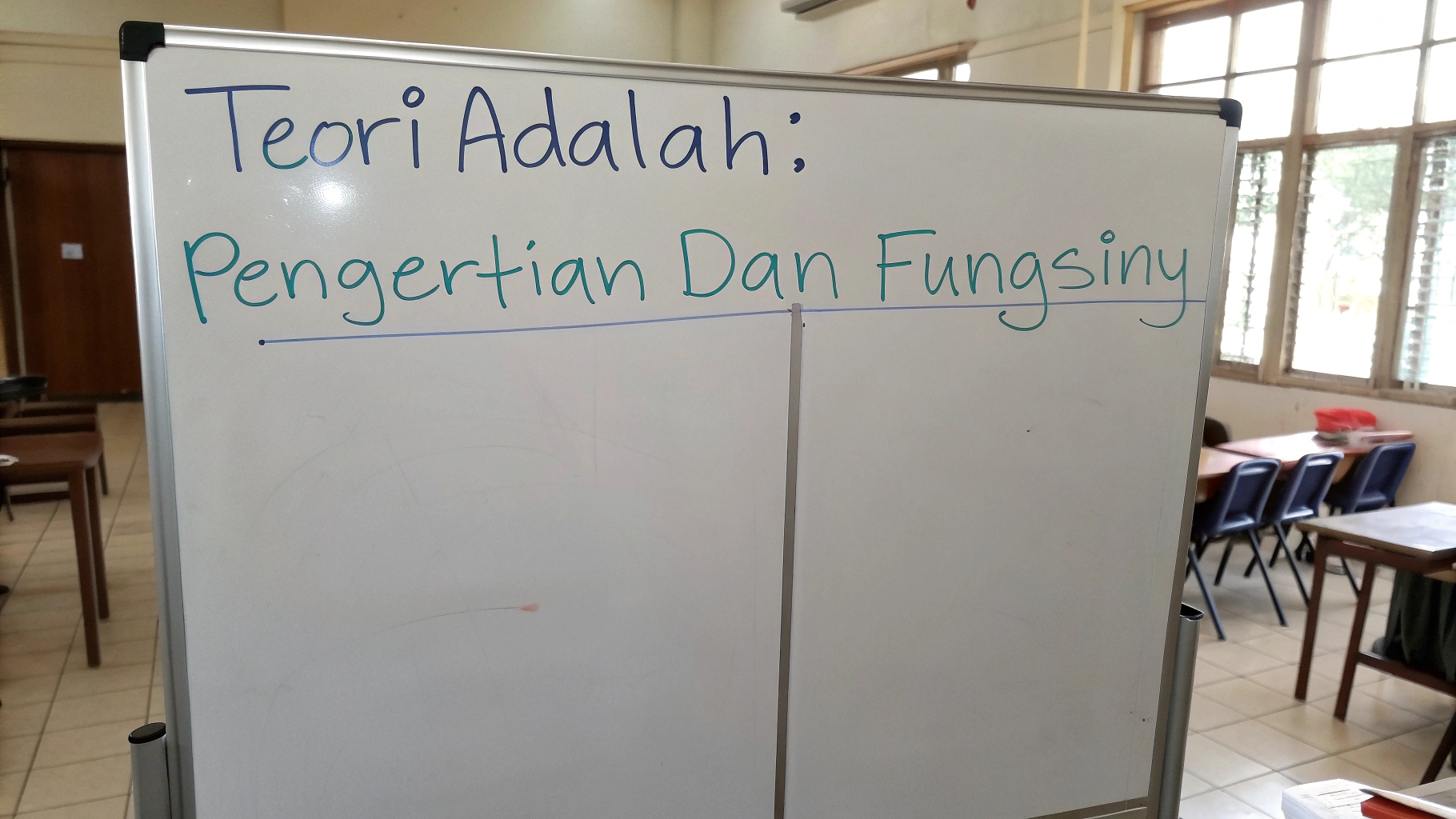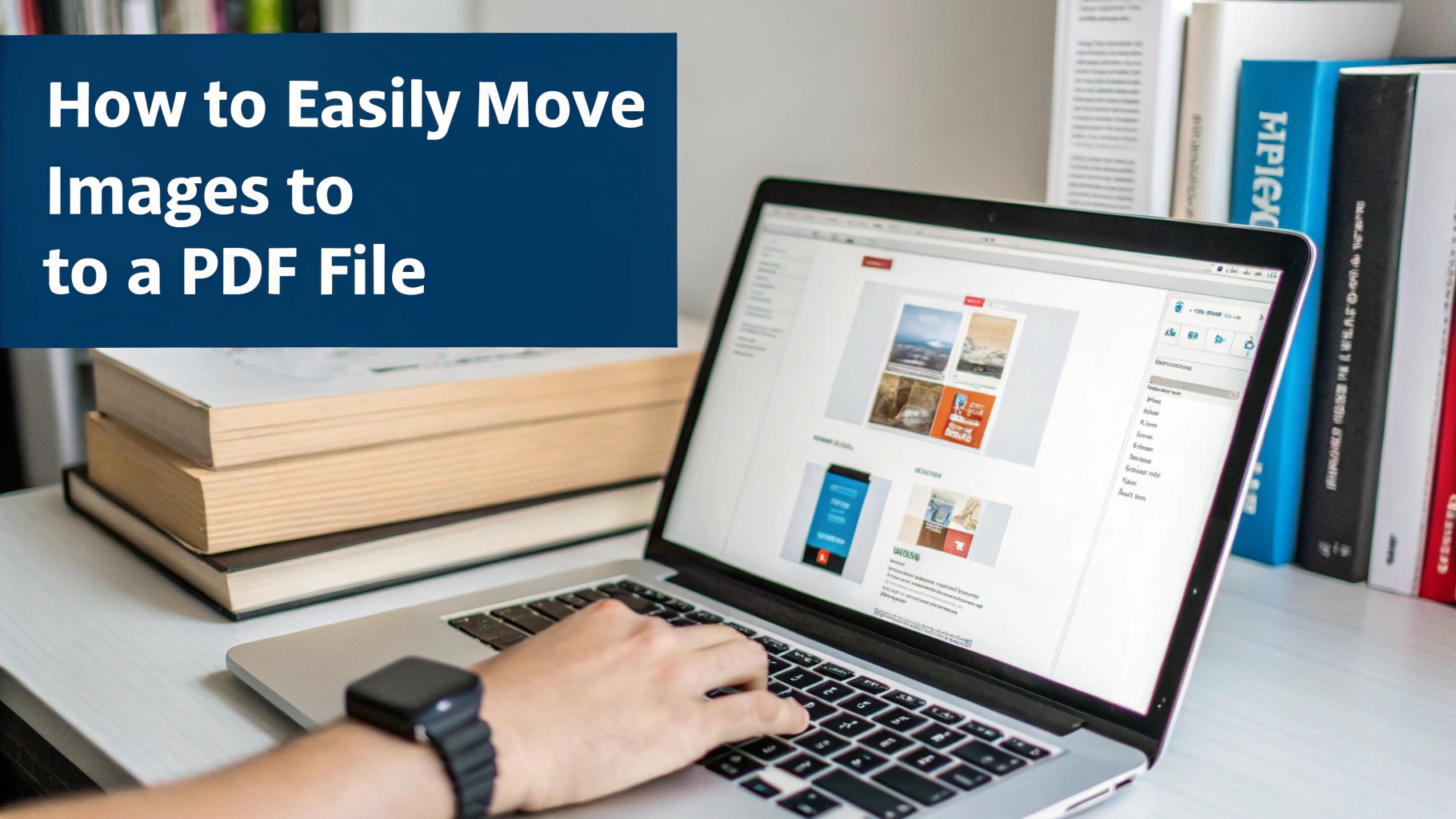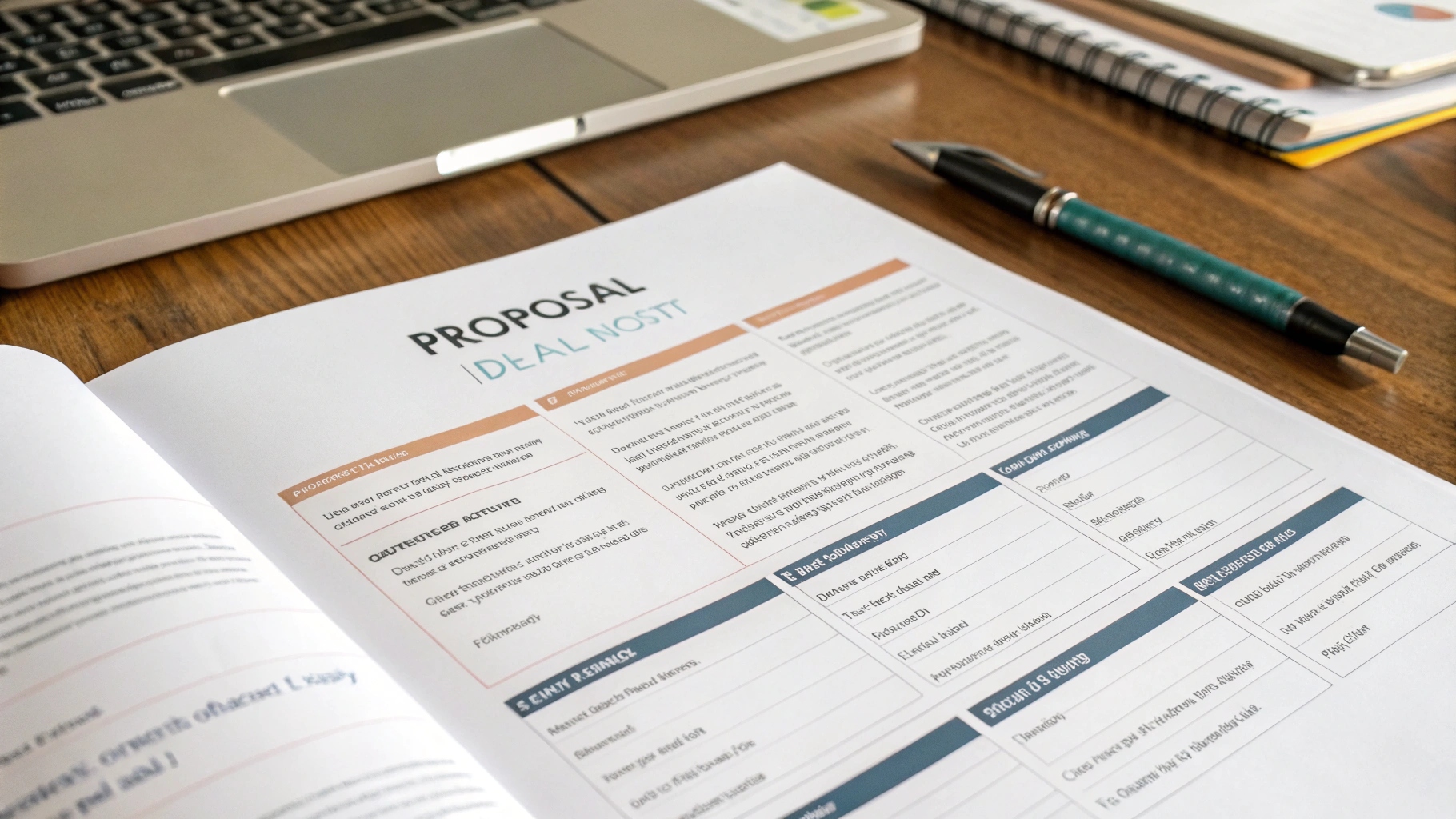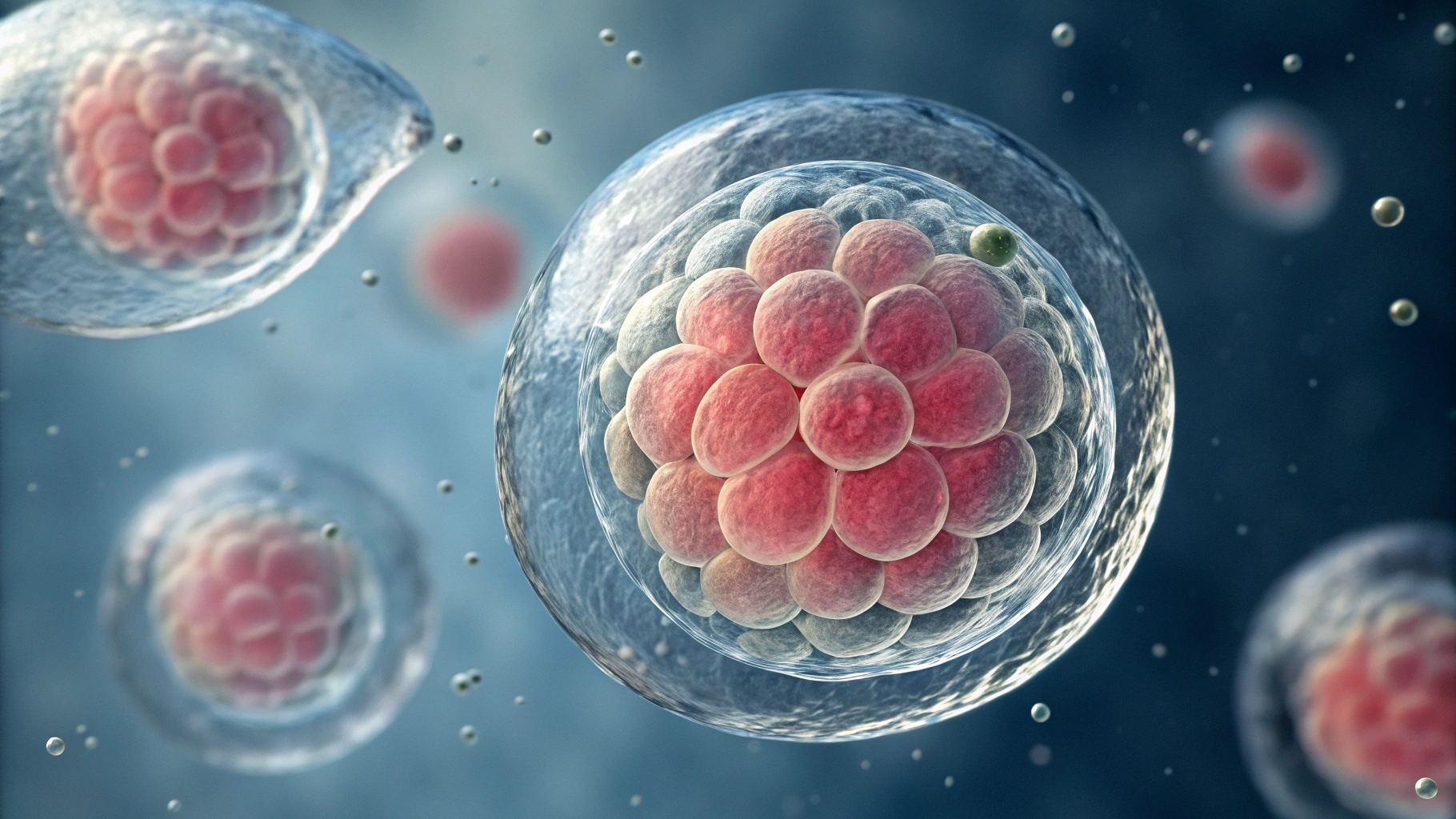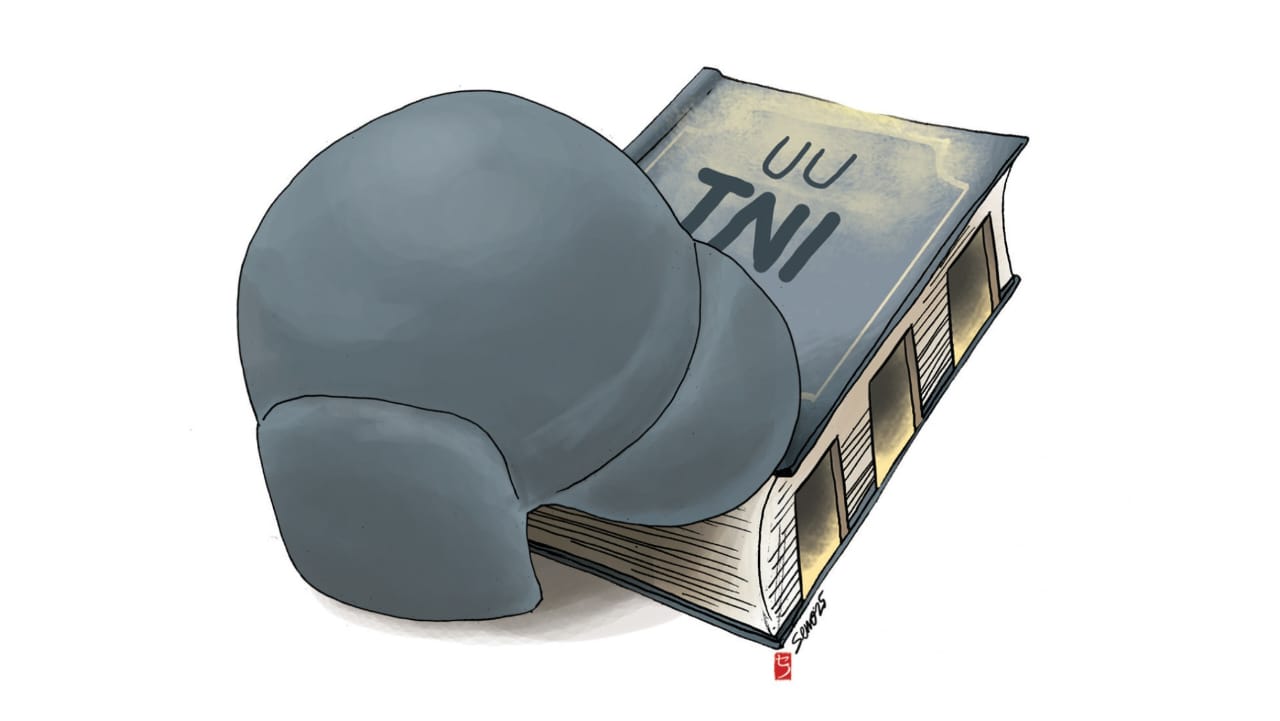 (MI/Seno)
(MI/Seno)
REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025. Meski mendapatkan kritik dari masyarakat sipil dan disambut dengan demonstrasi di berbagai kota, DPR dan pemerintah sepakat merevisi UU yang sudah berumur lebih dari 20 tahun tersebut. Kedua pihak menyebutkan bahwa perubahan itu tetap menjaga supremasi sipil, mendukung profesionalisme TNI, serta merespons perubahan ancaman yang dihadapi. Namun, tidak pernah dijelaskan secara jelas kegentingan apa yang mengancam sehingga prosesnya begitu cepat dan tidak transparan.
Dalam dua dekade terakhir, memang sudah terjadi perubahan dinamika ancaman di dunia. Ancaman dari aktor nonnegara seperti terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional, termasuk penyebaran narkotika dan kejahatan siber, cukup menjadi perhatian utama.
Sementara itu, aktor negara, terutama negara-negara adidaya, mulai mengembangkan strategi wilayah abu-abu (grey zone tactics), mulai serangan siber oleh Rusia hingga penggunaan milisi maritim oleh Tiongkok. Belum lagi, kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus memanas bisa mengarah kepada konflik terbuka di wilayah Indo-Pasifik.
Segala situasi tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan karakter ancaman, lompatan teknologi, bahkan cara berperang dilakukan sehingga penting bagi Indonesia untuk merancang kerangka regulasi yang adaptif dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Namun, berdasarkan sejarah TNI, perubahan dalam tubuh organisasi tidaklah menjawab ketiga tantangan yang disebutkan di atas. Perubahan haluan politik negara dan hubungan sipil-militer menjadi faktor utama, seperti doktrin dwifungsi di era Orde Baru hingga proses reformasi militer di awal 2000-an.
Revisi UU TNI 2025 menunjukkan gejala serupa, dengan upaya memperkuat profesionalitas TNI menghadapi perkembangan zaman tidak terasa. Meskipun perubahan Pasal 7 memasukkan ancaman terhadap pertahanan siber, pasal-pasal lain yang direvisi cenderung bersifat teknokratik dan administratif. Misalnya, pada Pasal 47 yang membahas jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif TNI, fokus revisi ialah menambahkan lembaga yang pada praktiknya sudah diisi perwira TNI. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk di atas 2004 sehingga tidak masuk UU TNI 2004. Penambahan usia pensiun bagi prajurit TNI juga justru berpotensi menghasilkan permasalahan baru berupa mandeknya proses promosi perwira.
UU PERTAHANAN NEGARA
Pemerintah dan DPR semestinya lebih dahulu merevisi UU Pertahanan Negara (Hanneg) untuk meredefinisi bagaimana negara kita merespons berbagai ancaman. Saat disahkan pada 2002, UU Hanneg menyebutkan dua kategori ancaman yang dihadapi Indonesia, yaitu ancaman militer dan nonmiliter.
Dalam menghadapi ancaman militer, TNI ditempatkan sebagai komponen utama, yang didukung komponen utama dan pendukung. Sementara itu, kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan menjadi unsur utama, yang dikoordinasikan pemimpin instansi sesuai dengan bidang mereka, dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman militer dijelaskan lebih jauh dalam tujuh jenis ancaman, tetapi tidak ada penjabaran lanjutan mengenai jenis-jenis ancaman nonmiliter.
Pemerintah menawarkan kategorisasi ancaman baru melalui UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) pada 2019. UU tersebut menambahkan ancaman hibrida sebagai ancaman yang dihadapi Indonesia. Kemudian disebutkan sekurangnya 15 jenis ancaman meskipun tidak secara jelas di bagian mana yang masuk kategori ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Di bagian penjelasan, ancaman hibrida diartikan sebagai ancaman yang bersifat gabungan antara ancaman militer dan nonmiliter. Dengan begitu, kerangka regulasi Indonesia masih belum secara jelas menjabarkan jenis ancaman yang masuk kategori ancaman nonmiliter serta ancaman hibrida.
Revisi UU TNI menjadi respons sangat terbatas pada kerangka doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut Indonesia. TNI, sebagai komponen utama dan unsur pendukung, hanyalah satu kepingan dari doktrin tersebut untuk menghadapi berbagai jenis ancaman. Jika pemerintah dan DPR serius menjawab perubahan ancaman, revisi UU Hanneg semestinya bisa digunakan seluruh pemangku kebijakan untuk meredefinisi ancaman dan respons yang proporsional. Kerentanan ekonomi yang kini menjadi topik utama persaingan geopolitik melalui perang tarif hingga isu keamanan energi dan pangan menunjukkan pendekatan pertahanan yang konvensional perlu dilengkapi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia bisa tetap dijaga.
Karena itu, revisi UU TNI ialah sebuah kesesatan cara berpikir dalam menghadapi perubahan situasi geopolitik dan dinamika ancaman. Tanpa mempersiapkan kerangka regulasi yang lebih menyeluruh, respons Indonesia bisa mengarah ke proses sekuritisasi dan pengerahan militer seakan-akan menjadi jalan keluar satu-satunya. Jika memegang teguh semangat reformasi, respons utama pemerintah semestinya memperkuat institusi sipil sebagai unsur utama menghadapi ancaman nonmiliter, bukannya membuka gerbang pelibatan militer yang semakin besar.
Respons berbagai negara demokratis terhadap ancaman hibrida juga menunjukkan tren serupa. Filipina mengutamakan kapal penjaga pantainya dalam merespons intrusi maritim dari Tiongkok ke wilayah lautnya. Sementara untuk kasus sabotase kabel bawah laut di Laut Baltik yang ditengarai dilakukan Rusia, negara-negara Eropa mengandalkan kerja sama polisi, intelijen, dan penjaga pantai lintas negara untuk memperkuat respons mereka. Bahkan untuk isu serangan siber, respons utama hampir semua negara terkecuali negara dengan kapasitas ofensif yang mumpuni seperti AS ialah dengan memperkuat instansi keamanan siber sipil mereka dan tidak serta-merta melibatkan angkatan bersenjata.
Berbagai kasus tersebut semestinya dipelajari secara mendalam terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR sebelum melompat pada pembahasan kilat merevisi UU TNI. Selain melalui revisi UU Hanneg, regulasi sektoral seperti rancangan UU Keamanan Laut dan Keamanan Siber Nasional perlu mendapatkan perhatian.
Dengan begitu, diharapkan Indonesia memiliki acuan regulasi terkait dengan gradasi ancaman untuk berbagai isu dan kepastian hukum di titik mana pelibatan TNI diperlukan. Tanpa sebelumnya memperbaiki kerangka tersebut, revisi UU TNI bukannya menjadi jawaban atas perkembangan ancaman, melainkan justru bisa menghadirkan kegagapan negara dalam kebijakan keamanan dan pertahanan ke depannya.
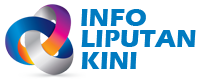
 2 weeks ago
16
2 weeks ago
16