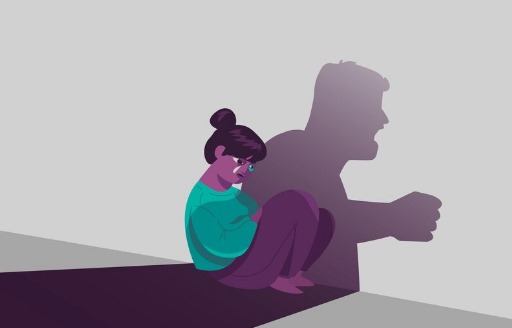Presiden AS, Donald Trump.(Dok. US Embassy Japan)
Presiden AS, Donald Trump.(Dok. US Embassy Japan)
KETUA Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno mengungkapkan kekhawatiran bahwa Indonesia berpotensi dikenakan tarif impor AS lebih tinggi, terutama setelah bergabung dengan BRICS.
Saat ini saja, katanya, tarif bea masuk produk Indonesia ke AS sudah mencapai 32%, ditambah potensi dikenakan 10% karena tergabung dalam BRICS.
"Kemungkinan kena tarif tinggi itu pasti ada. Saat ini saja, tarif bea masuk produk Indonesia ke AS sudah tinggi, totalnya bisa menjadi 42%," ujar Benny kepad Media Indonesia, Kamis (10/7).
Dia menjelaskan sejumlah komoditas yang paling rentan terdampak dari kebijakan tarif AS ini antara lain pakaian jadi, sepatu olahraga, komponen listrik, dan furnitur. Menghadapi kondisi ini, Benny menekankan pentingnya pengalihan pasar selain ke Amerika Serikat (AS).
“Diversifikasi pasar mutlak dilakukan untuk menjaga kinerja ekspor nasional,” ujarnya.
Risiko Besar
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin. Ia menilai risiko pengenaan tarif lebih tinggi terhadap Indonesia mungkin terjadi.
"Oleh karena itu, kita lihat bagaimana hasil diplomasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto," ucapnya.
Menurutnya, diperlukan diplomasi dan negosiasi intensif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di satu sisi, Saleh juga mendorong penguatan kerja sama di antara negara-negara BRICS.
“Komunikasi yang intens dengan sesama anggota BRICS penting agar dapat saling membuka pasar. Dengan begitu, ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS dapat berkurang ke depan,” tambahnya.
Terkait dampaknya, Saleh menerangkan kenaikan tarif impor AS tentu akan memengaruhi daya saing produk ekspor Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai US$28,18 miliar, tumbuh 9,27% dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi AS terhadap total ekspor nasional pun cukup besar, yakni 9,65%. Tambahan tarif pun dikhawatirkan akan menurunkan daya saing produk Indonesia.
“Harga barang ekspor Indonesia akan menjadi relatif lebih mahal, sehingga berdampak pada penurunan volume ekspor. Ini tentu akan merugikan industri dalam negeri yang berorientasi ekspor,” jelas Benny.
Dalam jangka panjang, penurunan ekspor ini juga bisa berdampak pada keuntungan industri dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya. Beberapa sektor utama yang rentan terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, serta perikanan, semuanya merupakan komoditas ekspor utama ke AS.
“Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada upaya antisipatif, potensi PHK di sektor-sektor tersebut sangat mungkin terjadi,” pungkasnya.
Wanti-wanti
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mewanti-wanti posisi Indonesia yang masuk anggota BRICS. Dia berpendapat pengenaan tarif tinggi oleh AS terhadap sejumlah negara anggota BRICS, seperti Brasil yang dikenai bea masuk 50% untuk produk baja, bukan sekadar kebijakan perdagangan semata. Ini melainkan bagian dari dinamika geoekonomi yang makin tegang.
"Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS memang patut dicermati dengan lebih hati-hati," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia.
Meskipun, lanjutnya, belum terdapat sinyal eksplisit bahwa Indonesia akan menjadi target tarif serupa, namun keikutsertaan dalam konsolidasi ekonomi alternatif terhadap hegemoni barat bisa saja menimbulkan konsekuensi terselubung, terutama bila Indonesia dianggap terlalu akomodatif terhadap kepentingan Tiongkok atau Rusia dalam forum tersebut.
Situasi ini menuntut pemerintah untuk membaca risiko bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari spektrum diplomatik dan geostrategis yang lebih luas. Kewaspadaan perlu diarahkan pada beberapa aspek. Yakni, Indonesia harus menghindari posisi yang terlalu bias secara geopolitik agar tidak dianggap sebagai pihak yang meninggalkan poros Barat sepenuhnya.
Kedua, diplomasi dagang harus diperkuat bukan hanya di BRICS, tetapi juga dengan mitra lama seperti AS dan Uni Eropa. Hal ini dalam rangka menegosiasikan kerangka preferensi tarif dan perlindungan pasar yang lebih adil.
"Ketiga, strategi diversifikasi ekspor tak bisa lagi sekadar jargon. Perlu ada penguatan hilirisasi dan orientasi ke pasar nontradisional secara sistematis," tutupnya. (H-3)
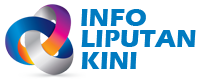
 3 months ago
31
3 months ago
31