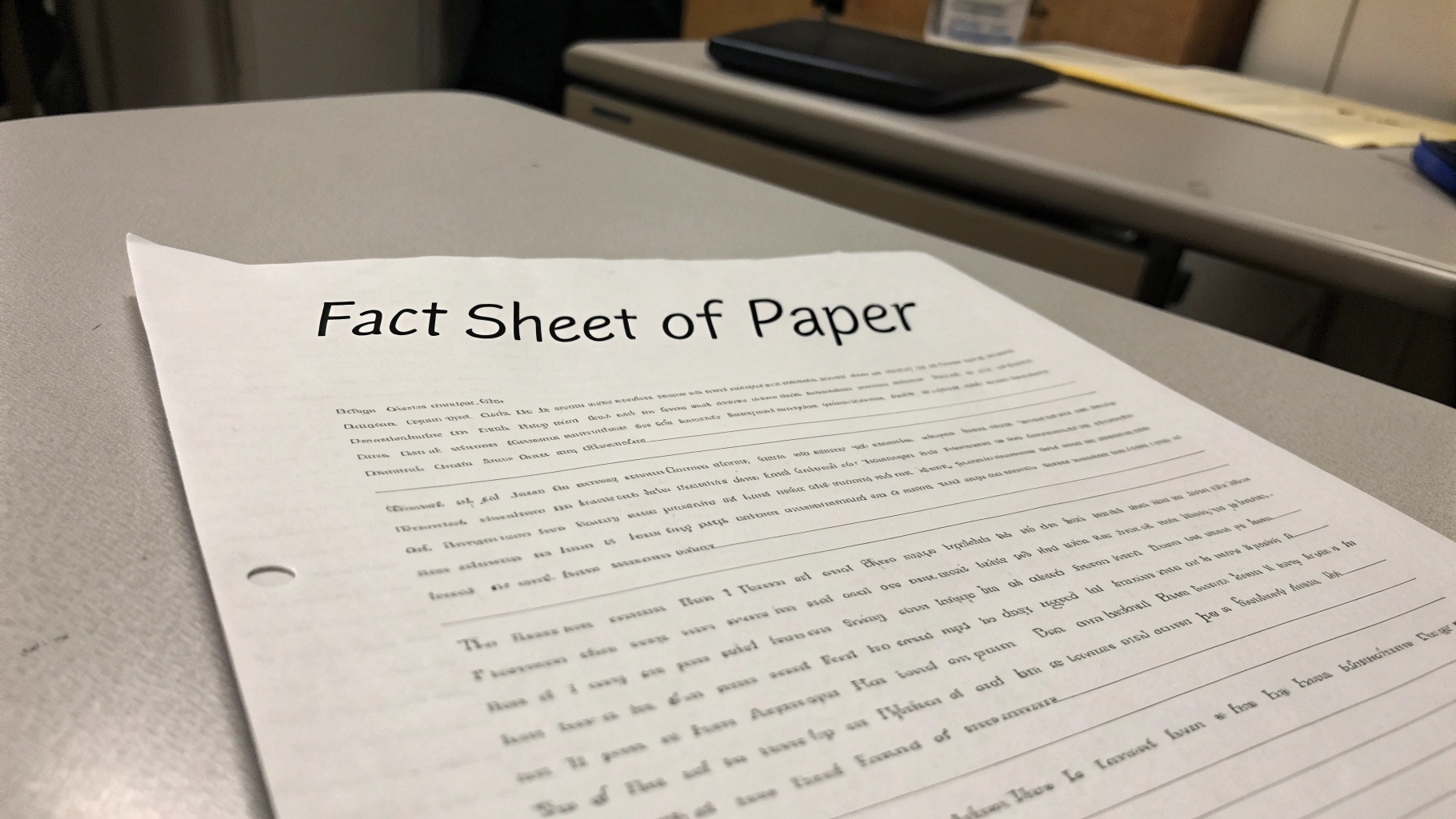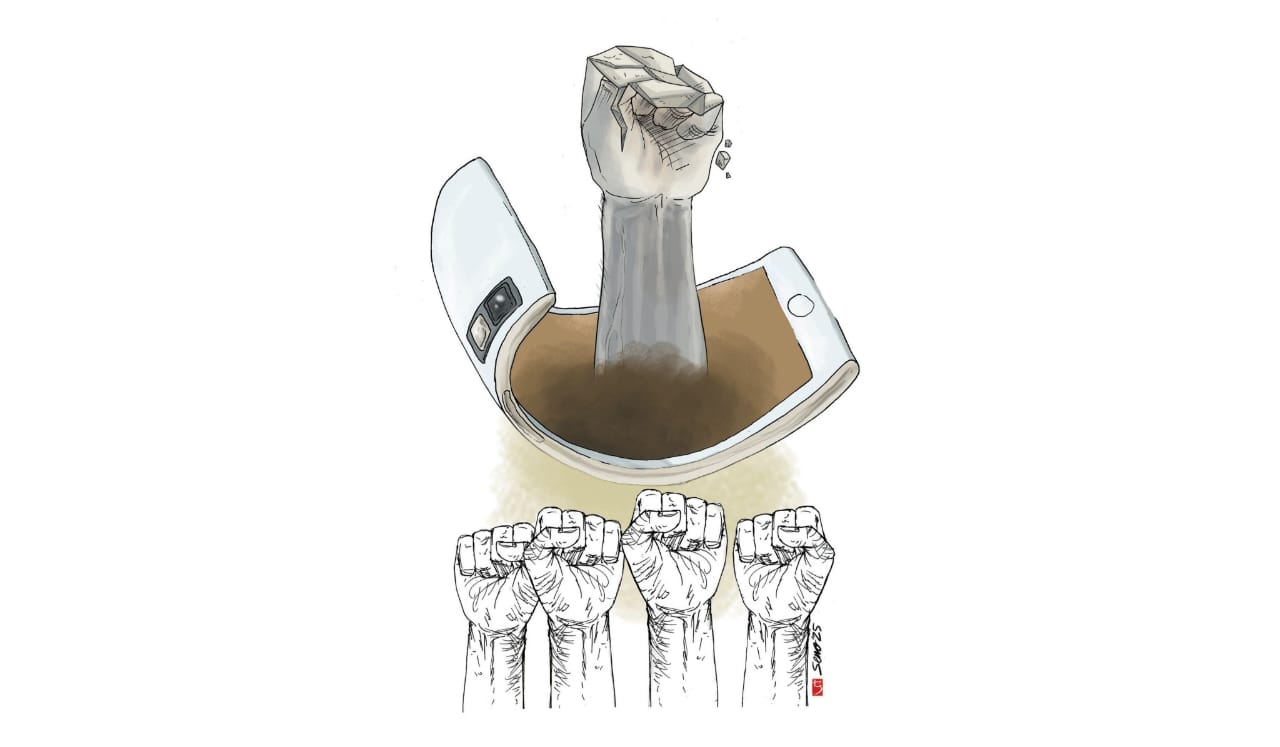 (MI/Seno)
(MI/Seno)
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi. Namun, Merlyna Lim dalam studinya tentang media sosial dan politik di Asia Tenggara menemukan hal sebaliknya. Pendapat yang menyebutkan media sosial meningkatkan partisipasi politik, menurut Merlyna Lim, terlalu menyederhanakan persoalan, mengabaikan interaksi rumit antara manusia dan teknologi.
"Digital technology was inherently never democratic. Teknologi digital tidak pernah demokratis dalam dirinya," kata Merlyna dalam diskusi bukunya, Social Media and Politics in Southeast Asia, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/4).
Merlyna, akademisi berkebangsaan Indonesia yang menyandang posisi sebagai Canada Research Chair dalam bidang media sosial, menjelaskan itu karena media sosial bekerja dengan algoritma, sedangkan manusia lebih mudah digerakkan perasaannya. Merlyna menyebutnya politik baper, politik membawa-bawa perasaan.
"Algoritma memanipulasi perasaan manusia untuk membeli satu merek atau produk, termasuk memilih kandidat dalam pemilu. Jadi algoritma diciptakan untuk kepentingan kapitalisme dan membangun digital authoritarianism, otoritarianisme digital," kata Merlyna.
Ia menerangkan hubungan timbal balik antara media sosial dan politik tidak terlepas dari peran algoritma teknologi digital dan perasaan manusia dalam membentuk cara kita mengonsumsi politik, menyebarkan dan memanipulasi informasi. "Pengaruh informasi tidak ditentukan kualitas, tetapi viralitas, popularitas, dan penyebarannya."
Mereka yang memiliki kapital ekonomi dan kekuasaan punya peluang lebih besar memanfaatkan algoritma media sosial untuk memanipulasi informasi. Mereka merekrut relawan, pendengung berbayar, atau pemengaruh untuk membuat informasi viral dan tersebar secara luas.
PENDENGUNG
Yatun Sastranidjaja dan Wijayanto melakukan studi penggunaan buzzer atau pendengung di Indonesia. Hasil studi mereka tertuang dalam monograf berjudul Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia's Cyberspace, yang diterbitkan ISEAS Yusuf Ishak Institute Singapura (2022).
Kedua peneliti menyelisik penggunaan buzzer di tiga kasus: revisi Undang-Undang KPK pada September 2019, kebijakan normal baru selama Covid-19 pada Mei 2020, dan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020.
Ringkasan studi mereka meliputi empat poin. Pertama, manipulasi opini publik dan propaganda terorganisasi meningkat di Indonesia. Terutama sejak 2019, kampanye buzzer meningkat signifikan, yang bertujuan memobilisasi konsensus publik untuk kebijakan kontroversial pemerintah.
Kedua, operasi buzzer memainkan peran penting dalam kasus kontroversial revisi UU KPK, new normal covid-19, dan UU Cipta Kerja, ketika publik bersikap kritis terhadap ketiga isu. Dalam ketiga kasus, terang benderang terbukti buzzer memanipulasi opini publik untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Ketiga, dalam ketiga kasus, buzzer secara sengaja membanjiri media sosial dengan narasi yang mempromosikan agenda elite pemerintahan, sering kali menggunakan pesan pelintiran dan disinformasi yang diamplifikasikan oleh banyak akun buzzer dan bot. Dengan begitu, buzzer efektif menenggelamkan narasi oposisi di media sosial serta pendapat berbeda dari media arus utama.
Keempat, penggunaan buzzer secara lebih sistematis mengindikasikan meningkatnya kooptasi ruang siber Indonesia untuk kepentingan elite politik.
Intinya, operasi buzzer mengancam kualitas demokrasi karena mereka tidak hanya menjejali opini publik dengan disinformasi, tetapi juga mencegah warga negara mengevaluasi dan mengkritik perilaku elite pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan.
Padahal, kelebihan demokrasi jika dibandingkan dengan sistem politik lain ialah demokrasi itu memiliki mekanisme koreksi diri (self-corrective mechanism). Kritik menjadi mekanisme koreksi diri bagi para elite.
DISINFORMASI POSITIF
Salah satu bentuk manipulasi informasi, kata Merlyna, ialah algorithmic whitebranding atau positive disinformation dalam kampanye. “Model kampanye white branding atau positive disinformation bersifat ahistoris, sebuah politik kegembiraan yang ahistoris,’’ ujarnya.
Merlyna mencontohkan bagaimana BongBong Marcos menggunakan disinformasi positif untuk memanipulasi perasaan rakyat Filipina melalui kampanye ’Backstories with Imelda Marcos, Project During Her Times as First Lady’. Di Indonesia, algorithmic whitebranding dipraktikkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui citra gemoi dalam kampanye Pemilu Presiden 2024.
Studi Merlyna menunjukkan penggunaan algorithmic whitebranding sebagaimana terjadi dalam kasus BongBong dan Prabowo paralel dengan logika komunikasi kapitalis dan kultur marketing algoritma. Algorithmic whitebranding secara strategis juga sukses memanipulasi emosi dan daya tarik individu, termasuk kaum milenial, yang berpartisipasi dalam politik bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai konsumen.
Algorithmic whitebranding atau positive disinformation menghasilkan pemimpin populis di berbagai belahan dunia. “Indonesia dapat Prabowo, Filipina dapat Marcos, India dapat Modi, dan Amerika dapat Trump,” kata Inaya Rakhmani, Assosiate Professor Departemen Komunikasi Universitas Indonesia dan Direktur Pusat Studi Asia Universitas Indonesia. Inaya menjadi penanggap dalam diskusi buku Merlyna Lim.
WARGA NEGARA BUKAN KONSUMEN
Merlyna Lim menegaskan kesuksesan algoritma memanipulasi perasaan manusia bukan sepenuhnya kesalahan algoritma tersebut. “Algoritma hanya setengah agensi. Tanggung jawab juga ada pada manusia,” katanya.
Merlyna melanjutkan, emosi rakyat gampang dimanipulasi algoritma karena rakyat memosisikan diri sebagai konsumen (consumers), bukan warga negara (citizens). Dia merekomendasi rakyat menjadi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik demi meningkatkan kualitas demokrasi.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia Hurriyah sepakat rakyat semestinya berpartisipasi dalam politik sebagai warga negara, bukan sebagai konsumen. “Bagaimana rakyat bisa berpartisipasi dalam politik sebagai warga negara, saya kira melalui pendidikan politik dan literasi digital,” ujar Hurriyah yang juga Direktur Pusat Studi Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.
Bagaimana bila demokrasi analog digunakan untuk melawan penggerusan demokrasi melalui media digital? Meski tidak dalam konteks politik, sejumlah negara mulai memberlakukan aturan analog untuk menghadapi dampak negatif media sosial. Siswa di Swiss, misalnya, kembali menulis dengan tangan dan baca buku cetak.
Janie Barlett dalam buku The People vs Tech (2018) betul-betul mengusulkan regulasi analog untuk melawan manipulasi algoritma dalam pemilu. Dia merekomendasi komisi pemilihan umum, misalnya, mengharuskan media sosial mencatat dan melaporkan penggunaan platform mereka untuk iklan politik.
Regulasi juga mengharuskan kandidat, partai politik, atau peserta pemilu melaporkan akun-akun di media sosial yang digunakan untuk kampanye politik, serupa kandidat atau partai politik mendaftarkan juru kampanye mereka kepada komisi pemilihan umum. Dengan transparansi, pengawas pemilu, masyarakat sipil, pers, dan akademisi bisa menganalisis dan mengekspos berbagai bentuk pelanggaran.
Intinya, untuk berpartisipasi dalam politik, cara-cara analog masih perlu digunakan guna mengimbangi penggunaan teknologi digital. Unjuk rasa di depan gedung parlemen ternyata efektif menggagalkan upaya merevisi Undang-Undang Pilkada akhir tahun lalu, selain tagar ‘Indonesia Darurat’.
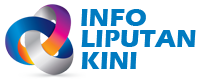
 1 week ago
19
1 week ago
19