 Professor Iman Harymawan, Ketua PUI PT Bisnis Berkelanjutan, Universitas Airlangga.(Dok. Pribadi)
Professor Iman Harymawan, Ketua PUI PT Bisnis Berkelanjutan, Universitas Airlangga.(Dok. Pribadi)
Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu biodiversity hotspot dunia, berada pada posisi strategis untuk tidak hanya menjadi pelaksana ibadah haji, tetapi juga pemimpin dalam membangun ekosistem investasi berkelanjutan di sektor haji dan umrah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan haji tidak hanya tentang pelayanan jemaah, tetapi juga tentang bagaimana investasi strategis dapat menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bermakna. Momentum transformasi global, terutama melalui kerangka Saudi Vision 2030, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi bagian aktif dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah, yang kini menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi Arab Saudi.
Saudi Vision 2030 secara eksplisit menempatkan industri haji dan umrah sebagai penggerak ekonomi yang modern, efisien, dan berorientasi layanan. Regulasi baru di Arab Saudi juga memberikan ruang bagi partisipasi swasta dan investor internasional untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur, logistik, dan layanan berbasis digital bagi jemaah. Bagi Indonesia, peluang ini sangat strategis. Kita bukan hanya mengirim jutaan jemaah setiap tahun, tetapi juga memiliki potensi besar untuk ikut berperan dalam berbagai aspek rantai nilai ekosistem haji. Mulai dari layanan transportasi dan akomodasi ramah lingkungan, penyediaan produk halal, hingga inovasi teknologi dan solusi keberlanjutan di Tanah Suci.
Namun, di sisi pengelolaan dana haji, masih terdapat tantangan yang perlu dikaji secara serius. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menjalankan mandatnya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kepatuhan syariah, namun belum sepenuhnya mengarahkan dana haji ke sektor-sektor investasi produktif dan berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola, koordinasi lintas lembaga, serta digitalisasi dalam pengelolaan investasi masih perlu diperkuat. Dari perspektif strategi ESG, ada ruang besar untuk memperluas portofolio ke investasi yang tidak hanya aman dan patuh syariah, tetapi juga memberi dampak positif secara sosial dan lingkungan.
Jika kita melihat lebih luas, Indonesia memiliki sejumlah pilar ekosistem yang potensial untuk dikembangkan dalam konteks investasi haji dan umrah. Pertama, infrastruktur hijau dan layanan ramah lingkungan yang mendukung kenyamanan jemaah sekaligus menjaga kelestarian alam, seperti transportasi rendah emisi dan pengelolaan limbah di kota suci. Kedua, rantai suplai halal dan ekonomi umat, di mana Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai global hub produk halal dan layanan berbasis nilai-nilai Islam. Ketiga, transformasi digital dan inovasi pelayanan jemaah, termasuk penggunaan teknologi data besar, AI, dan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keempat, kolaborasi akademik dan penelitian lintas lembaga untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan standar keberlanjutan yang jelas. Terakhir, penguatan dimensi keberlanjutan dan impact investing agar setiap rupiah investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.
Dari evaluasi strategi investasi yang ada, terlihat bahwa portofolio dana haji masih perlu diarahkan secara lebih sistematis menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. BPKH bersama para pemangku kepentingan perlu menyusun peta jalan jangka panjang yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam seluruh keputusan investasi. Ini mencakup audit strategis terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek, pembentukan kemitraan global dengan investor dan lembaga penelitian, serta komunikasi publik yang transparan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat. Selain itu, potensi revenue stream dari ekosistem haji dan umrah dapat diperluas melalui kerja sama dengan Arab Saudi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi pelayanan jemaah, maupun sektor halal hospitality yang kini berkembang pesat.
Sudah saatnya Indonesia mengambil peran sebagai pemimpin dalam investasi haji dan umrah yang berkelanjutan. Pengelolaan dana haji tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan keuangan semata, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak luas bagi umat. Pemerintah dan regulator perlu memberikan insentif bagi investasi hijau, digital, dan inklusif sosial di sektor ini. Dunia akademik dan lembaga riset harus hadir untuk memberikan masukan berbasis data dan mengembangkan kerangka ESG yang sesuai dengan konteks keumatan.
Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kokoh antara BPKH, Kementerian Agama, industri keuangan syariah, investor, dan perguruan tinggi untuk membangun fondasi ekosistem investasi yang berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam, tetapi juga membuktikan bahwa ibadah haji dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan alam. Dengan visi yang jelas, tata kelola yang kuat, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Indonesia berpeluang menjadi thought leader global dalam investasi ekosistem haji dan umrah yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan. (Z-10)
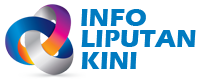
 7 hours ago
2
7 hours ago
2
















































